Lima hari setelah tulisan ini terbit, negeri kita menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.
Siapa yang Anda pilih tergantung hati nurani masing-masing. Apakah akan memilih mantan presiden, presiden yang masih berkuasa, atau “calon” presiden.
Semua terserah Anda, tak ada yang memaksa. Jikalau keterpaksaan yang mendesak Anda menentukan salah satu kandidat, maka pilihan Anda akan ‘ternodai’. Proses yang bermula dari sebuah noda akan menghasilkan noda pula.
Beberapa pekan sejak KPU menetapkan pasangan calon presiden-wakil presiden, kita dijejali beragam rupa dan corak unjuk diri mereka. Di televisi, koran, majalah, radio dan di jalanan. Potret yang memasang senyum, menjual tampang, mengobral janji, mengharap dukungan, memenuhi otak di tengah kesulitan hidup yang kian mendera.
Masing-masing calon mengaku punya resep jitu guna menyejahterakan rakyat, mengangkat harkat dan martabat bangsa, menciptakan keadilan, juga memberantas korupsi. Semuanya masih berupa janji, masih sekadar “jika”, “seandainya”, “seumpama” dan cucu moyangnya.
Padahal salah satu calon pernah berkuasa, dua lainnya malah kini sedang berkuasa. Lantas apa yang dilakukan? Kenapa harus menunggu terpilih lagi untuk melakukan perubahan? Kenapa tidak berbuat ketika tengah berkuasa? Lima tahun lalu, janji serupa pernah diikrarkan. Namun, apa hasilnya?
Sebagian besar rakyat negeri ini masih berkubang dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Sementara kesenjangan antara si kaya dan si miskin begitu mengangga. Jaraknya melebihi panjangnya Jembatan Suramadu yang baru saja diresmikan.
Lalu apa yang diharapkan dari proses demokratisasi yang katanya mulai membaik. Di mana rakyat bisa memilih langsung presiden yang diinginkannya. Dimana vox populi vox dei adalah sistem ‘terbaik’ pemerintahan manusia.
Padahal kata-kata Alcuinus, sang sejarawan dan rohaniawan, dalam suratnya kepada Charlemagne, Raja Frank itu; ada awal dan akhirnya. Tidak hanya pada ‘populi’ dan ‘dei’. Ia menulis, “Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit.”
“Jangan dengar kata-kata orang yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan, karena kericuhan massa selalu dekat dengan kegilaan!” Kita tentu saja tak ingin disebut gila karena ribut mengurusi pencontrengan, dan menganggapnya sebagai ‘titah’ Tuhan.*
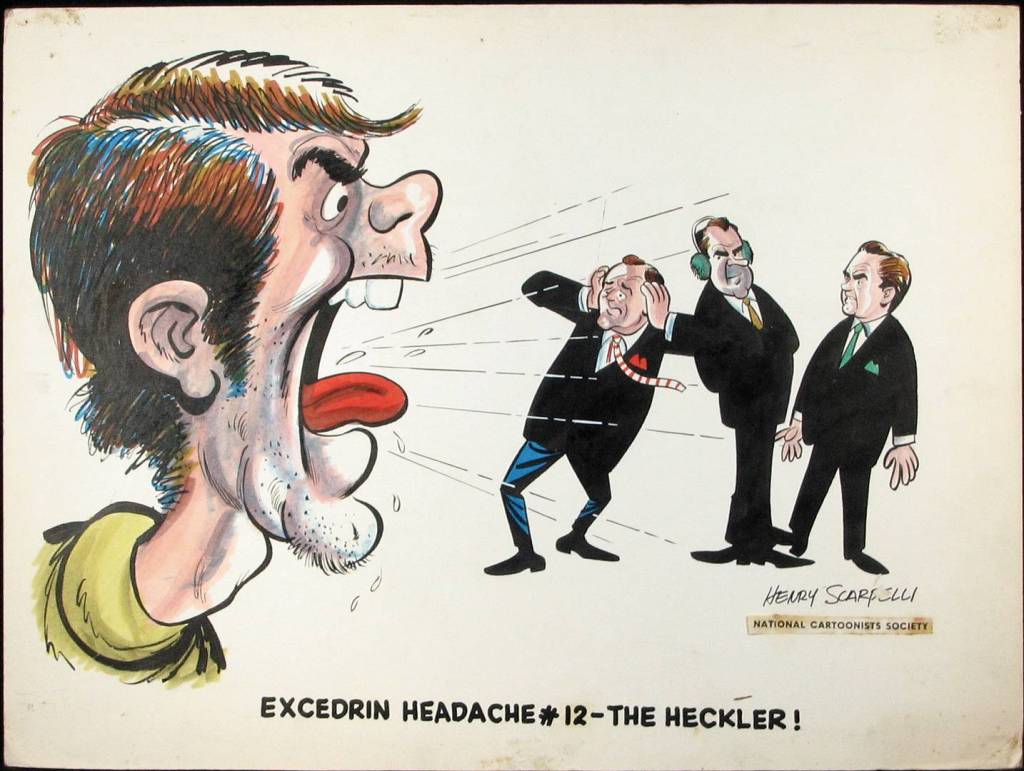
Leave a comment